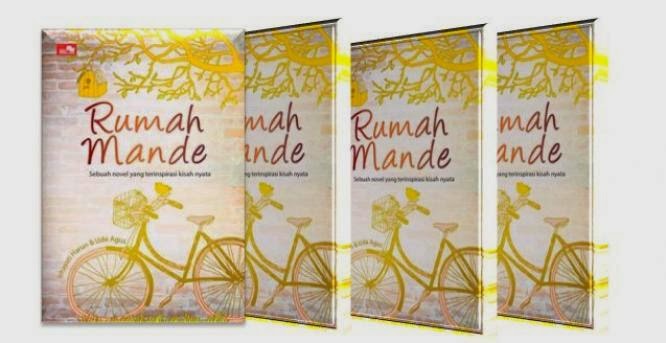Tidak ada yang istimewa dari wanita yang akan kujadikan pendamping hidupku ini. Wajahnya rata-rata, kulitnya coklat tua, dengan rambut sebahu yang tidak terlalu hitam. Badannya juga tak seputih dan setinggi mantan-mantan kekasihku. Tapi entah mengapa aku jatuh hati padanya, meski baru beberapa hari mengenalnya.
Sekali lagi, aku tidak main-main untuk menjadikannya sebagai istriku! Meski teman-temanku tak berhenti menyindirku dengan mengatakan, aku kena peletlah! Aku patah hatilah! Dan segala macam sindirin yang membuatku semakin tak ingin mundur dari niatku semula, untuk menikahi Lilis, gadis gunung yang sederhana.
Aku tahu, keputusanku ini terlalu terburu-buru. Mungkin karena Lilis begitu perhatian padaku, juga dengan anggota keluargaku.
Maklumlah! Sebagai anak sulung yang begitu dibanggakan dan diharapkan sebagai tulang punggung keluarga, aku harus tetap menunjukkan perhatian dan tanggung jawabku sebagai anak yang baik. Otomatis orang yang akan mendampingi hidupku kelak, haruslah wanita yang bisa menerima anggota keluargaku, terutama ibu. Dan Lilis melakukan itu semua diawal perkenalan kami. Setiap kubawa kerumah, dia tak pernah bertangan kosong. Ada saja oleh-oleh yang ia beli buat Ibu dan adik-adikku. Sikapnya juga begitu ramah pada Ibu, serta mampu mendekatkan diri dengan ketiga orang adikku
Adapun alasan yang lain karena aku bersimpati padanya. Selama ini dia hidup sebatang kara. Kakek yang merawatnya sedari kecil sudah meninggal dunia karena sakit. Sedangkan neneknya sudah wafat terlebih dulu. Lilis sendiri sedari kecil sudah tak memiliki ibu. Ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Sedangkan bapaknya, pergi begitu saja tanpa kabar berita. Mungkin menikah lagi aku tak tahu pasti. Yang aku tahu dari cerita Lilis, ayahnya menitipkan dirinya pada kakeknya sebelum pergi merantau ke Jakarta. Itulah alasan yang membuatku menerimanya.
Setelah menikah, baru kusadari bahwa Lilis begitu pencemburu. Mulanya Lilis cemburu pada semua wanita yang pernah dekat padaku. Aku maklumi, karena itu artinya dia begitu mencintaiku. Tapi disaat dia cemburu pada teman-teman priaku, aku merasa dia tak hanya sekedar cemburu. Sikapnya sudah mengarah pada prilaku possesif!. Mulanya aku tertekan, karena merasa Lilis sudah kelewatan.
Setelah merenung, aku pun mencoba mau mengerti. Mengingat kami masih pengantin baru. Mungkin Lilis tak ingin waktuku lebih banyak kuhabiskan tanpa dirinya disampingku. Lagi-lagi aku turuti maunya, untuk lebih memilih tinggal dirumah bersamanya.
Barangkali masalalunya yang pahit membuatnya takut kehilangan orang yang ia cintai, batinku. Akupun berusaha menghibur hatiku. Sejak menikah, aku tak lagi ngumpul-ngumpul dengan teman-teman gengku. Sepulang bekerja, aku langsung mendekam dirumah. Meski dihari libur sekalipun. Aku juga harus bisa menerima, saat teman-temanku mengatakan bahwa aku telah berubah seratus delapan puluh derajat! Tak lagi gaul seperti dulu.
Suatu hari Lilis mengetahui bahwa aku telah memberi uang belanja pada Ibu.
“Lilis ingin Aa’ memberi uang pada Ibu dan adik-adik lewat tangan Lilis,” ucapnya tegas.
“Apa maksud Lilis?” tanyaku menyelidik.
“Lilis merasa tersinggung kalau Aa’ memberikan uang pada Ibu dan adik-adik tanpa sepengetahuan Lis. Lilis kan kakak ipar mereka?” Begitu katanya saat aku bertanya alasannya.
Benar juga, pikirku. Seharusnya, aku tak menaruh prasangka negatif padanya. Untuk seterusnya, kupercayakan uang belanja dan biaya sekolah adik-adikku padanya.
Belakangan ini aku sering pulang lebih larut karena lembur. Badanku rasanya sakit semua. Seperti biasanya, Ibu akan memijatku penuh kasih sayang. Setelah badanku enakan, aku segera menemui Lilis di kamar. Sambutan Lilis tak seperti biasanya, yaitu penuh kelembutan. Dia juga tak menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Yang ada wajahnya kusut dan tak berkata sepatah katapun padaku. Tak salah lagi, Lilis ngambek!
Aku yang tak betah melihat sikapnya seperti itu, segera mencercanya dengan berbagai pertanyaan. Tapi Lilis tetap bungkam, membuatku semakin tak enak hati. Karena tak tahan lagi, akupun mengancam akan tidur diluar. Akhirnya Lilis membuka suara, meskipun sambil menangis.
“Lilis memang istri yang tak bisa menyenangkan hati Aa’. Dimata Aa’, Lilis hanyalah istri yang tak berguna!”
“Mengapa Lilis berpikiran seperti itu?” tanyaku heran.
“Mengapa tak meminta Lilis saja yang memijat badan Aa’? Memangnya, pijatan Lis tidak enak?” ucapnya sambil menangis.
“Bukan Aa’ tak percaya sama Lilis. Aa sudah terbiasa dipijat Ibu sedari kecil. Ya sudah! Besok-besok Lilis saja yang memijat Aa,” jawabku merasa bersalah. Lilis pun kembali tersenyum mendengarnya.
Walau harus kuakui, tak ada yang bisa mengalahkan enaknya pijatan Ibu. Tapi aku berusaha untuk menahan diri--untuk tidak memberitahu Lilis yang sebenarnya-- kalau pijatan tangannya, tak senikmat dan sehangat pijatan tangan ibu.
Kisah kecemburuan Lilis tak berhenti sampai disitu. Selalu ada hal-hal kecil yang membangkitkan rasa cemburunya. Misalnya saat aku membelikan adik perempuanku sate ayam di hari libur. Lilis akan cemberut melihatnya. Padahal hal itu sudah aku lakukan sebelum menikah dengannya. Tak pelak, dia pun melontarkan sindiran-sindiran tajam. Atau tatkala aku membelikan hadiah buat adik lelakiku, saat dia meraih rangking pertama disekolahnya. Lilis terang-terangan menunjukkan sikap tak sukanya.
Dilain waktu ketika aku membelikan Ibu sepasang busana muslimah, Lilis terlihat sewot dan mengatakan, “Aa’ tidak adil! Mengapa Lilis tak dibeliin juga?” Akhirnya, aku pun membelikan busana muslimah yang sama buatnya.
Lilis kembali mencemburui sikapku yang begitu perhatian pada Ibu dan ketiga adikku. Padahal dari awal dia sudah tahu posisiku sebagai anak tertua, yang harus tetap menyayangi dan menafkahi keluarga, meskipun sudah menikah.
Mungkinkah sikap manis Lilis dulu pada keluargaku hanyalah basa-basi semata? Demi menarik simpati keluarga besar kami agar dirinya diterima? Akh… tak pantas kau berprasangka buruk pada istrimu. Hanya akan mengotori hatimu saja. Bisik hati nuraniku. Aku pun kembali membuang pikiran jelekku pada Lilis.
Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan, pikirku. Aku harus mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Baik buat Lilis, juga buat Ibu dan adik-adikku. Dengan terpaksa, aku melakukan hal yang sebenarnya tak ingin kulakukan--agar adik-adik dan Ibu tak lagi menjadi korban kecemburuan Lilis. Mungkin hidup berjauhan, akan menjauhkan konflik yang semakin sering terjadi diantara mereka.
“Ibu keberatan kalau kamu keluar dari rumah ini. Selain Ibu tak ingin berjauhan denganmu, siapa yang akan menjaga adik-adikmu? Ibu tak sanggup menanggung beban hidup sendiri semenjak ditinggal Bapakmu,” Ibu berkata sambil tersedu.
“Siapa bilang aku akan menelantarkan Ibu dan adik-adik begitu saja? Aku akan sering kemari Bu, meski kita tak lagi tinggal seatap.”
Ibu akhirnya setuju, walau aku tetap melihat keberatan itu dimatanya. Aku merasa keputusanku ini sudah tepat. Setelah beberapa hari mempertimbangkannya.
Semula dengan mengontrak rumah sendiri aku bisa bernafas lega, tak lagi capek meladeni sifat pencemburu Lilis, istriku. Kenyataannya, sifat pencemburu Lilis tidak hilang juga. Kali ini kecemburuan Lilis pada Ibu dan adik-adikku beralih sementara pada tetangga sebelah rumah kontrakan kami.
“Aa’ lihat enggak? Ros tetangga sebelah rumah kita baru saja membeli televisi yang layarnya datar. Bagus deh A’. Dia bilang, harganya tidak terlalu mahal kok,” ucap Lilis sambil melendot-lendot padaku. Aku sudah bisa menebak isi hati Lilis. Pasti dia ingin aku membelikannya juga. Meski aku sudah pura-pura tidak perduli dengan permintaannya, Lilis tak putus asa untuk terus mendesakku.
“Jadi, kapan Aa’ mau beliin Lis?” pintanya sambil merajuk.
“Iya secepatnya,” jawabku lembut. Aku pun kembali tak berdaya, untuk tidak memenuhi keinginannya. Terpaksa uang tabungan aku ambil sedikit demi sedikit untuk memenuhi rasa cemburunya.
Dilain waktu, Lilis kembali minta dibeliin handphone. “Lis ingin punya handphone yang ada kameranya A’, seperti punya si Ros.”
“Buat apa Lis? Bukankah handphone yang lama sudah cukup?” jawabku sambil menggerutu.
“Kalau Aa’ tidak mau beliin Lis, ya sudah!” ucapnya sambil merengut dan langsung mengunci diri di kamar. Seperti biasanya, Lilis pun menjalankan aksinya-- mogok bicara denganku selama beberapa hari. Terang saja aku tidak tahan didiamkan oleh istri sendiri. Kembali kuturuti kemauannya. Akhirnya, aku kembali menuruti semua kemauan Lilis yang dilandasi rasa cemburu yang membabi buta itu.
Kecemburuan Lilis untuk memiliki barang-barang seperti milik tetangga terus berlanjut. Aku dibuat lelah lahir dan batin dibuatnya. Mungkin benar kata Ibu, kalau badanku semakin hari semakin kurus seperti orang yang banyak pikiran. Sebetulnya, aku ingin berterus terang pada Ibu bahwa aku sering makan hati dengan tingkah laku Lilis. Tapi, aku berusaha berdalih karena kelelahan bekerja. Sebab aku tak ingin menambah beban pikiran Ibu.
Sementara uang yang aku gunakan untuk membeli semua barang permintaan Lilis adalah uang yang aku tabung untuk membetulkan rumah Ibu yang sudah rusak disana-sini. Aku berniat mengganti genteng yang bocor dengan asbes. Belum lagi bila hujan datang, Ibu dan adik-adikku harus tidur diruang tamu karena kamarnya basah.
Tak hanya mengganti genteng yang lama dengan yang baru. Kamar mandi juga sudah tak layak lagi untuk dipakai. Karena sudah tumbuh lumut disana sini. Aku berniat melapisi dindingnya dengan keramik. Dapur Ibu juga sudah jelek. Aku berniat akan membuatkan tungku yang baru untuk Ibu memasak.
Untuk menebus rasa bersalahku pada Ibu, akupun lebih giat lagi mencari uang, dengan mencari kerja sampingan. Setelah satu tahun uang pun terkumpul. Akupun mencatat berapa pengeluaran untuk merenovasi rumah Ibu. Setelah kurasa cukup, akupun segera memberitahu Ibu berita yang sangat ia nantikan ini. Ibu menitikkan air mata bahagia, saat tahu impiannya akan segera terwujud. Untuk memiliki rumah yang lebih layak bagi dirinya dan anak-anaknya.
Disaat Ibu tengah diliputi perasaan bahagia, tak begitu halnya dengan Lilis. Dia sedikitpun tak menunjukkan rasa senang, saat kuceritakan tentang niatku untuk mempercantik rumah Ibu.
“Harusnya Aa’ tahu, sebentar lagi kita akan memiliki seorang anak. Kebutuhan bayi kan banyak sekali!” ucapnya ketus.
“Tapi Aa’ sudah lama punya janji pada Ibu. Gak enak kalau harus menunda lagi. Aa’ rasa, gaji bulanan Aa’ masih cukup untuk membeli keperluan kamu dan anak kita, disaat melahirkan nanti,” jawabku agak jengkel. Tega-teganya Lilis mempermasalahkan yang sudah menjadi hak Ibu.
Aku tahu, pasti Lilis marah sekali padaku, karena aku tak mau mengikuti keinginannya kali ini. Tapi aku tak perduli lagi. Bagiku, ini sudah kewajiban seorang anak lelaki pada Ibunya. Apapun komentar Lilis, aku tak akan menggubrisnya.
Namun yang terjadi sungguh tak kuduga sebelumnya. Mulanya Lilis menangis seharian. Aku berusaha tak perduli! Karena aku tahu Lilis pintar bermain sandiwara. Besok-besoknya, dia berubah menjadi pendiam. Aku tak berminat menanyakannya, karena aku sudah jenuh dengan segala taktik yang dia mainkan selama ini. Namun saat dia sering berbicara sendiri, aku tidak bisa tinggal diam. Bagaimanapun, dia tetap istriku. Apapun bentuk kesalahannya. Apalagi dia tengah mengandung anakku. Aku pun kembali bersikap lembut padanya. Dan mencoba mengorek isi hatinya, mengapa akhir-akhir ini dia bertingkah seperti orang yang kurang waras. Tapi Lilis malah menjerit histeris. Tanpa menunggu lagi, akupun membawanya berobat ke psikiater.
“Tampaknya istri anda mengalami depresi yang cukup berat.”
“Akhir-akhir ini istri saya sering diliputi rasa cemburu. Mungkin rasa cemburu butanyalah yang telah membuatnya jadi begini, Dok!”
“Maksud Anda apa? Mungkin bisa Anda ceritakan secara lebih mendetail lagi.”
“Kecemburuan istri saya yang sangat besar, telah membutakan mata hatinya, hingga tak bisa melihat kebahagiaan orang lain. Termasuk kebahagiaan Ibu mertuanya sendiri Dok.” Dokter pun akhirnya bisa mengerti, setelah aku bercerita panjang lebar padanya, tentang perasaan cemburu Lilis yang sudah melampaui batas ini.
Sore ini setelah pulang dari rumah sakit, dengan langkah berat aku mengunjungi rumah Ibu untuk memberitahukan sebuah berita yang tidak ingin aku sampaikan. Sebab aku tahu pasti, berita ini akan sangat mengecewakan bagi Ibu dan adik-adikku.
“Karena bolak-balik membawa Lilis berobat ke psikiater, akhirnya uang untuk membangun rumah Ibu terpaksa aku gunakan dulu. Maafkan Asep Bu, karena belum bisa memenuhi harapan Ibu. Tapi Asep berjanji akan tetap memenuhi harapan Ibu suatu hari nanti,”
Dengan berat hati, kusampaikan pada Ibu masalah yang sebenarnya. Ibu mau mengerti meski aku tahu, betapa hancurnya hati Ibu.
dimuat di majalah alia